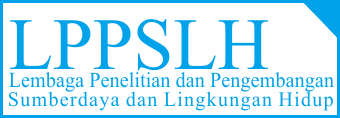Sistem irigasi dapat diterjemahkan sebagai upaya manusia memodifikasi distribusi air, yang terdapat dalam saluran alamiah, dengan menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk memanipulasi seluruh atau sebagian air untuk keperluan produksi tanaman pertanian (Small dan Svendsen, 1995; Sinulingga, 1997). Pengertian tersebut dengan jelas memperlihatkan adanya unsur fisik sekaligus unsur kelembagaan yang saling terkait dalam suatu sistem irigasi. Unsur fisik adalah infrastruktur yang digunakan dalam mengambil/menyalurkan air dari sumber air; sementara unsur kelembagaan adalah proses memfasilitasi dan mengendalikan pergerakan air mulai dari sumbernya hingga ke petakan lahan.
Merujuk pada pengertian sistem irigasi di atas, Small dan Svendsen (1995) menguraikan tiga subsistem yang ada dalam sistem irigasi, yaitu: (1) subsistem akuisisi, yang mencakup unsur fisik dan kelembagaan yang berkaitan dengan penangkapan air dari sumbernya; (2) subsistem distribusi, yang mencakup unsur-unsur yang terkait dengan pergerakan aliran air dari sumbernya ke pinggir petakan tempat air akan digunakan; dan (3) subsistem aplikasi, yang terdiri atas unsur-unsur yang terkait dengan pengaplikasian air ke tanah (lihat Gambar 1 di bawah ini).
Secara keseluruhan sistem irigasi teknis merupakan suatu bangunan irigasi yang dimulai dari suatu daerah bendungan dan menyebar ke berbagai daerah pertanian melalui saluran-saluran pembagi primer sampai kuarter. Sementara secara institusional, pengelolaan irigasi bersifat lintas sektoral. Setidaknya terdapat dua departemen sekaligus dua sistem, yaitu sistem irigasi dan sistem pertanian. Patut dipahami bahwa suatu sistem irigasi hanya mempersoalkan penyaluran air (subsistem distribusi) dari sumbernya (subsistem akuisisi) hingga ke petakan lahan pertanian (subsistem aplikasi). Sementara proses budidaya tanaman di lahan-lahan yang memperoleh air irigasi sudah bukan masalah sistem irigasi lagi, melainkan sistem pertanian. Secara ideal, antara dua departemen (terutama di tingkat pelaksana lapangan) harus terjadi arus informasi yang baik. Dengan demikian, informasi mengenai kondisi ketersediaan air dan proses penyalurannya bisa dijadikan rujukan bagi strategi pola tanam.
Kajian mengenai sistem irigasi memerlukan kemampuan untuk memahami adanya kaitan yang erat antara sistem irigasi dengan sistem-sistem lainnya. Sistem pertanian tentu saja merupakan sistem terdekat dengan irigasi, sebab air irigasi ditujukan untuk produksi pertanian. Namun, bila pembahasan sudah masuk ke wilayah keterkaitan antara sistem irigasi dengan produksi pertanian, maka kita sudah mulai beranjak memasuki persoalan sistem ekonomi pertanian. Sebagai contoh, kurangnya air pada suatu irigasi ternyata dapat menyebabkan penurunan hasil bahkan kegagalan dalam penyemaian.
Penurunan hasil atau kegagalan dalam penyemaian berarti pula gangguan yang besar bagi pendapatan ekonomi rumah tangga petani. Apabila kemudian gangguan dengan pola tersebut menimpa banyak petani, tentu saja akan mempengaruhi sistem perekonomian desa. Keterkaitan ini jika terus diurut ke tingkat yang lebih besar, akan menuju ke arah sistem ekonomi-politik. Tentu saja faktor-faktor input lain bagi sistem perekonomian di luar sistem irigasi harus dipertimbangkan pula. Keterkaitan antarsistem dari sistem irigasi dengan sistem lainnya pada akhirnya akan menunjukkan suatu tinjauan menyeluruh mengenai pentingnya persoalan irigasi bagi kehidupan petani.